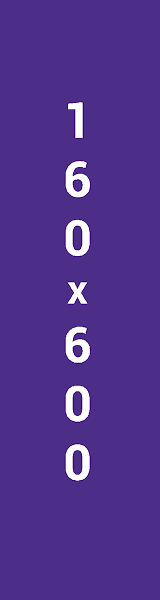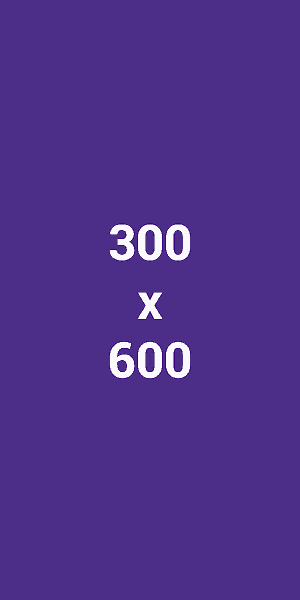Sayangnya, struktur dan sistem sepak bola di China tidak berkembang. Jumlah pemain muda berbakat terlalu sedikit, intervensi politik terlalu besar, dan korupsi masih merajalela.
Wang Xiaolei, komentator sepak bola lainnya, menyebut bahwa budaya sepak bola tak sejalan dengan sistem pendidikan dan pemerintahan China yang kaku dan menekankan hafalan.
"Sepak bola butuh kreativitas dan semangat, bukan dogma," tulisnya dalam sebuah blog.
Kekalahan Demi Kekalahan
Kekalahan memalukan 0-7 dari Jepang tahun lalu menunjukkan betapa terpuruknya timnas China. Padahal, Jepang adalah rival geopolitik utama.
China hanya pernah lolos satu kali ke Piala Dunia, yaitu tahun 2002, dan saat itu mereka kalah di semua laga tanpa mencetak satu gol pun. Saat ini, peringkat FIFA mereka di posisi 94 — bahkan di bawah Suriah yang dilanda perang.
Sebagai perbandingan, Islandia dengan jumlah penduduk hanya sekitar 400 ribu sudah pernah tampil di Piala Dunia.
Bahkan saat ini, tidak ada satu pun pemain China yang bermain di liga top Eropa. Hanya Wu Lei, pemain terbaik mereka, sempat bermain tiga musim di La Liga bersama Espanyol — klub yang sebagian sahamnya juga dimiliki investor China.
Meski Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, peluang China tetap kecil. Jika kalah dari Indonesia, mereka dipastikan tersingkir. Kalaupun menang, mereka harus kembali menang atas Bahrain pada 10 Juni agar bisa melaju ke babak selanjutnya.
Budaya Sepak Bola yang Terhambat
Rowan Simons, komentator asal Inggris yang sudah 40 tahun tinggal di China, menyebut bahwa reformasi yang mewajibkan sepak bola di sekolah memang membantu.
Tapi menurutnya, budaya sepak bola sejati tumbuh dari relawan, masyarakat sipil, dan klub independen — yang semuanya tidak bisa berkembang di bawah kendali Partai Komunis.
"Di usia 12 atau 13 tahun, ketika anak-anak masuk SMP, tekanan akademis langsung meningkat. Sepak bola pun ditinggalkan," jelasnya.